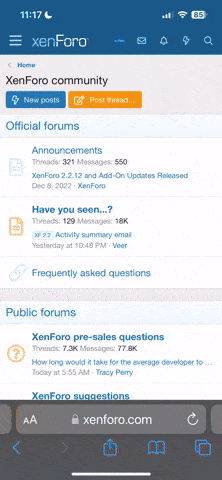Prolog
LEONARDO VETRA, seorang ahli fisika, mencium aroma
daging terbakar. Dia tahu yang terbakar itu adalah tubuhnya
sendiri. Dengan penuh ketakutan dia menatap sosok hitam yang
membungkuk kepadanya. ”Apa maumu?”
”La chiave,” jawabnya dengan suara parau. ”Kata kuncinya.”
”Tetapi ... aku tidak—”
Penyusup itu menekankan benda itu lebih kuat sehingga benda
panas itu masuk lebih dalam lagi ke dada Vetra. Terdengar suara
mendesis yang keluar dari daging yang terpanggang.
Vetra menjerit kesakitan. ”Tidak ada kata kuncinya!” Dia merasa
dirinya sebentar lagi hampir pingsan.
Mata orang itu melotot, ”Ne avevo paum. Itu yang kutakutkan.”
Vetra berusaha untuk tetap sadar, namun kegelapan telah
menyelimutinya. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah
dia tahu orang yang menyerangnya itu tidak akan memperoleh apa
yang dicarinya. Sesaat kemudian, sosok itu mengeluarkan sebilah
pisau dan mendekatkannya ke wajah Vetra. Pisau itu terayun
dengan cermat dan menyayat seperti pisau bedah.
”Demi kasih Tuhan!” jerit Vetra. Sayang, sudah terlambat.[]
TINGGI DI ATAS puncak anak tangga Great Pyramid Giza,
seorang perempuan muda tertawa dan berseru ke bawah kepada
seorang lelaki. ”Robert, cepatlah! Aku tahu aku semestinya
menikah dengan lelaki yang lebih muda!” Senyum perempuan itu
begitu memesona.
Robert berjuang untuk mengimbanginya, tapi tungkai kakinya
seperti terpaku. ”Tunggu,” pintanya. ”Kumohon ....”
Ketika lelaki itu berusaha mendaki, pandangannya mulai
mengabur. Dia seperti mendengar suara-suara di telinganya. Aku
harus menangkap perempuan itu! Tapi ketika dia mendongak lagi,
perempuan itu telah menghilang. Di tempat di mana perempuan
itu sebelumnya berada, berdiri seorang lelaki tua dengan gigi yang
berwarna kecokelatan. Lelaki tua itu menatap ke bawah, ke
arahnya, dan tersenyum penuh kesedihan. Kemudian dia menjerit
keras penuh penderitaan sehingga menggema ke seluruh padang
pasir.
Robert Langdon tersentak bangun dari mimpi buruknya. Telepon
di samping tempat tidurnya berdering. Dengan linglung dia
mengangkatnya.
”Halo?”
Aku mencari Robert Langdon,” suara seorang lelaki berkata.
Langdon duduk tegak di atas tempat tidurnya dan mencoba
menjernihkan pikirannya. ”Ini Robert Langdon.” Dia menyipitkan
matanya ketika menatap jam digitalnya. Pukul 5.18 pagi.
”Aku harus bertemu denganmu segera.”
”Siapa ini?”
”Namaku Maximilian Kohler. Aku seorang ahli fisika partikel.”
”Apa?” Pikiran Langdon masih kacau. ”Kamu yakin saya Langdon
yang kamu cari?”
”Kamu dosen ikonologi religi di Harvard University. Kamu
menulis tiga buku tentang simbologi dan—”
”Kamu tahu jam berapa sekarang?”
”Maafkan aku. Tapi aku mempunyai sesuatu yang harus kamu
lihat. Aku tidak dapat membicarakannya lewat telepon.”
Langdon mendesah maklum. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya.
Salah satu risiko menjadi penulis buku-buku tentang simbologi
religi adalah telepon dari para penganut sebuah agama yang fanatik
yang ingin agar ia membenarkan keyakinan mereka kalau mereka
baru saja menerima pertanda dari Tuhan. Bulan lalu, seorang
penari telanjang dari Oklahoma menjanjikan pelayanan seks habishabisan
kalau Langdon mau terbang ke rumahnya untuk
memeriksa keaslian dari bentuk salib yang secara ajaib muncul di
atas sprei tempat tidurnya. Kain Kafan dari Tulsa, begitu Langdon
menyebutnya.
”Bagaimana kamu mendapatkan nomor teleponku?” tanya
Langdon mencoba bersikap sopan walau orang itu meneleponnya
pada waktu yang sungguh tidak sopan.
”Dari internet. Dari situs bukumu.”
Langdon mengerutkan keningnya. Dia sangat yakin situs bukunya
tidak mencantumkan nomor teleponnya. Lelaki itu pasti
berbohong.
”Aku harus bertemu denganmu,” desak orang itu. ”Aku akan
membayarmu dengan harga yang pantas.”
Sekarang Langdon mulai kesal. ”Maafkan aku, tetapi aku
betulbetul—”
”Jika kamu segera berangkat, kamu akan tiba di sini pada—”
”Aku tidak mau pergi ke mana -mana! Ini jam lima pagi!” Langdon
menutup teleponnya dan menjatuhkan dirinya lagi di atas tempat
tidur. Dia menutup matanya dan mencoba tidur kembali. Tidak
ada gunanya. Mimpi itu masih membayanginya. Dengan enggan,
dia mengenakan jubah kamarnya dan turun ke lantai bawah.
Robert Langdon berjalan mondar-mandir dengan bertelanjang kaki
di rumah bergaya zaman Victoria miliknya yang lengang di
Massachusetts dan menikmati ramuan ”sulit tidur” kesukaannya—
secangkir besar Nestles Quik panas. Sinar rembulan di bulan April
tampak menembus masuk dari jendela rumahnya yang menjorok
ke luar dan memberikan sentuhan tersendiri pada permadani
oriental yang terhampar di lantai. Rekan-rekan Langdon sering
mengoloknya dengan mengatakan rumahnya lebih mirip sebuah
museum antropologi daripada sebuah rumah. Rak bukunya
dipenuhi oleh berbagai artifak religius dari seluruh penjuru dunia,
seperti ekuaba dari Ghana, salib emas dari Spanyol, patung berhala
dari Aegean Selatan, dan bahkan tenunan langka bernama boccus
dari Kalimantan yang merupakan simbol keabadian usia muda
milik seorang ksatria.
Ketika Langdon duduk di atas peti kuningan Maharesi-nya dan
menikmati minuman cokelat hangat kesukaannya, kaca jendela
yang menjorok itu memantulkan bayangan dirinya. Bayangan itu
tampak berubah dan pucat ... seperti hantu. Hantu tua renta, katanya
seperti mengejek dirinya sendiri dengan berpikir jiwa mudanya
telah berlalu meninggalkannya.
Walaupun tidak terlalu tampan menurut ukuran biasa, Langdon
yang berusia empat puluh tahun ini memiliki apa yang disebut
rekan kerja perempuannya sebagai daya tarik ”seorang
terpelajar”—rambut cokelat tebal yang mulai tampak beruban,
mata biru yang tajam menyelidik, suara yang berat sekaligus
menawan, dan senyuman menggoda milik seorang atlet kampus.
Sebagai man tan anggota regu selam di sekolah lanjutan dan
perguruan tinggi, Langdon masih memiliki tubuh yang gagah
setinggi 180 sentimeter dan tetap terjaga berkat latihan renang yang
dilakukannya setiap hari sebanyak lima puluh putaran di kolam
renang kampus.
Teman-teman Langdon selalu menganggapnya sebagai orang yang
agak membingungkan—seseorang yang terperangkap di antara
abad yang satu dengan abad yang lainnya. Pada akhir pekan,
Langdon sering terlihat mengenakan jeans, duduk-duduk santai di
alun-alun kampus sambil berdiskusi tentang grafik komputer atau
sejarah agama dengan para mahasiswa; di lain waktu dia terlihat
mengenakan jas wol rancangan Harris, dan rompi dari wol halus
seperti yang terlihat dalam berbagai foto di halaman majalah seni
ternama ketika hadir dalam pembukaan museum untuk
memberikan pidato.
Walau dianggap sebagai dosen yang keras dan sangat disiplin,
Langdon juga dipuji sebagai orang yang suka bergembira. Dia
sangat menyukai kegiatan rekreasi sehingga diterima di lingkungan
mahasiswanya dengan baik. Julukannya di kampus adalah ”si
Lumba-lumba” karena sifatnya yang ramah dan karena
kemampuannya yang legendaris dalam menyelam dan berenang
ketika bertanding dalam pertandingan polo air.
Ketika Langdon duduk sendirian dan menatap ke dalam kegelapan,
kesenyapan rumahnya terusik lagi. Kali ini oleh suara dering mesin
faksnya. Merasa terlalu lelah untuk diganggu, Langdon hanya
berusaha untuk tertawa sendiri.
Umat Tuhan ini, katanya dalam hati. Sudah dua ribu tahun menunggu
Mesiah untuk menyelamatkan mereka, masih saja keras kepala seperti batu.
Dengan letih dia mengembalikan cangkir besarnya ke dapur dan
berjalan perlahan menuju ruang kerjanya yang memiliki dinding
yang berlapis kayu ek. Lembaran faks yang baru tiba itu tergeletak
di atas meja. Sambil mendesah, dia memungut kertas itu dan
mengamatinya.
Tiba-tiba dia merasa mual.
Gambar yang tertera pada lembaran itu adalah gambar sesosok
mayat manusia. Mayat itu ditelanjangi, dan kepalanya diputar
hingga sepenuhnya mengarah ke belakang. Ada luka bakar yang
parah di dada mayat itu. Lelaki itu diberi cap ... hanya satu kata
yang tertera di sana. Langdon mengenalinya dengan baik. Sangat
baik. Dia menatap huruf ornamen itu dengan rasa tidak percaya.